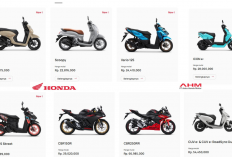Siapa Membunuh Putri (27) – Melamar Inayah

--
Oleh: Hasan Aspahani
”SAYA dulu ketika masih aktif sebagai wartawan pernah ditugaskan di sini,” kata ayah Inayah. Kami berbincang di restoran Hotel Nagata Plaza, sambil sarapan. Orang tua Inayah memilih menginap di hotel di tengah kota. Katanya, ia ingin melihat seperti apa dulu kota yang tapak awalnya ia saksikan.
”Beberapa kali saya pernah wawancara dengan Pak Habibie, orang jenius itu.” Ia tunjukkan fotonya bersama sosok yang pemikirannya membuat pulau ini berkembang seperti sekarang.
”Tak menyangka kota ini menjadi seperti ini sekarang,” kata ayah Inayah, ”benar-benar seperti kata penyair Idrus Tintin, disulap!”
Kami bicara tentang kota ini seperti dikarbit, matang tak merata. Matang terpaksa. Perkembangan yang di luar dari apa yang direncanakan. Judi, premanisme, pejabat korup, hukum yang mudah dibelok-bengkokkan, persoalan lahan tak habis-habis. Ekonomi memang tumbuh. Bisnis maju. Gedung-gedung megah bermunculan. Tapi kota ini juga jadi tong sampah. Apa-apa yang hendak disingkirkan dan di buang dari negeri seberang.
”Kesalahan atau kenaifan beliau adalah itu, Nak Abdur, ia pikir semua bisa ia kendalikan. Padahal tidak. Saya tahu betul soal itu. Nak Abdur juga pasti tahu,” katanya.
”Itu yang membuat saya tak betah sampai akhirnya saya memilih kembali ke Pekanbaru. Menjadi dosen. Jadi PNS. Dan menikah. Saya agak menikah, lambat juga punya anak. Inayah lahir tiga tahun setelah kami menikah, hampir empat tahun,” katanya.
Kami berbincang tentang banyak hal, kami bisa berbagi banyak cerita tentang dunia kewartawanan. Zain Azhar adalah wartawan yang disegani pada masanya. Ia seorang pencerita yang baik. Ia kenal petinggi-petinggi koran kami, teman-teman lamanya. Di Borgam, dia menyebut beberapa nama tokoh, pejabat, polisi, wartawan lama, dan pengusaha yang ia kenal. Ia menyebut juga nama Pak Rinto. Rinto Sirait. Si supir presiden. Inayah dan ibunya sesekali menimpali.
”Nak Abdur orang tuanya di mana sekarang?” tanya ayah Inayah.
Inilah bagian yang kucemaskan. Kepada orang lain saya bisa mengarang atau menghindar. Tapi ini yang bertanya adalah Zain Azhar, ayah Inayah.
”Mas Abdur yatim piatu sejak tujuh tahun, Yah,” kata Inayah, membantu saya memulai cerita.
”Iya, Pak. Ayah meninggal ketika saya tujuh tahun. Ibu bahkan tak pernah saya kenal, kecuali lewat foto saat ayah dan ibu bersanding,” kataku. Saya berusaha menceritakannya dengan biasa saja. Saya paling tak suka dikasihani orang. Saya malas menceritakan kisah masa kecil saya kalau hanya membuat orang mengasihani saya.
Ibu saya meninggal ketika melahirkan adik saya. Saat itu saya masih dua atau tiga tahun. Ayah menikah lagi dengan sepupu ibu. Sebagai ibu pengganti, bibi saya itu merawat saya seperti anak sendiri. Saya bahkan tak tahu bahwa dia adalah ibu tiri sampai dia memberitahukannya. Ayah meninggal karena kecelekaan di kapal. Ayah petani, sesekali melaut, sebagaimana banyak penduduk di kampung kami, kampung petani dan nelayan di pesisir Kalimantan. Ayah punya kapal kecil bermesin tempel. Suatu pagi dia pergi melaut ketika kabut pekat menyamarkan jarak pandang. Udara laut lebih dingin dari biasanya.
”Sarung yang ia lingkarkan di leher, terlilit roda gila. Ayah mati tercekik, terapung-apung sampai ada nelayan lain yang menemukan ayah,” kataku.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: